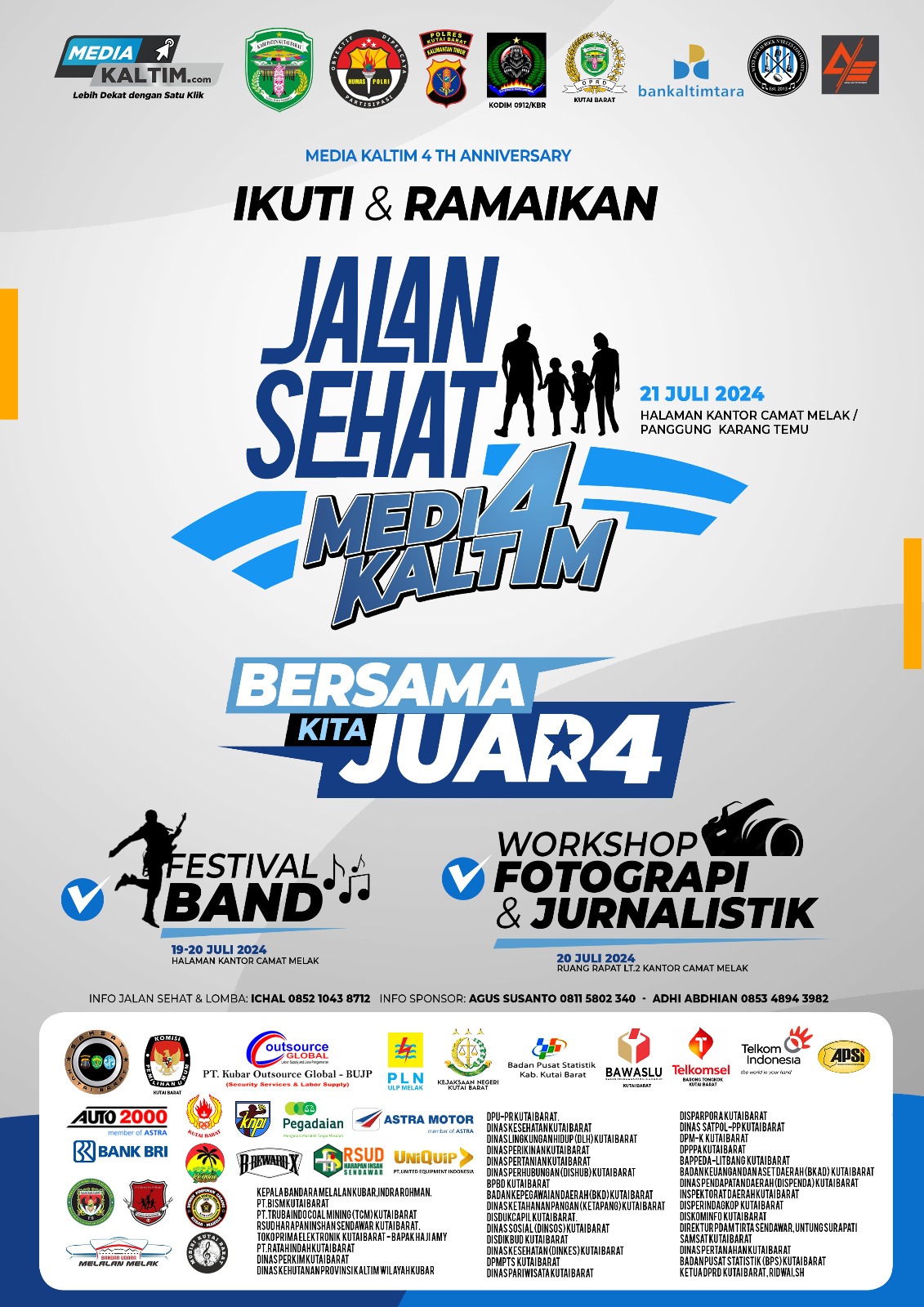Oleh: Awang Farrell Muhammad; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman. Email: awangfarrell22@gmail.com
Pendahuluan
Perkembangan era globalisasi terus membawa berbagai perubahan, kemajuan, dan tantangan secara bersamaan. Seiring berjalannya waktu, jarak yang memisahkan berbagai negara semakin menghilang, membuat berbagai budaya menjadi lebih dekat dari sebelumnya dan meningkatkan interaksi antar individu di dalamnya (Luthfia, 2011; Luthfia, 2014).
Dengan perubahan yang ada, masyarakat dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang semakin kompleks dalam menciptakan interaksi yang tepat dan efektif dalam keragaman, baik itu berupa suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain (Neal et al., 2013; Barrett et.al., 2014; Perry & Southwell, 2011).
Berkaitan dengan hal tersebut, telah banyak dilakukan penelitian untuk mengatasi permasalahan yang ada. Akibatnya, ada satu keterampilan khusus dan penting yang diperlukan dalam menghadapi perbedaan budaya, yaitu Intercultural Communication Competence (ICC) (Pinto, 2018; Penbek, ahin, & Cerit, 2012; Martin & Nakayama, 2015) .
ICC sendiri didefinisikan oleh Penbek, ahin, dan Cerit (2012) sebagai kemampuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang menjadi terbuka dan fleksibel terhadap budaya lain. Hal ini telah menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk bertahan hidup dalam masyarakat global di era ini.
Huang et al dalam Penbek, ahin, dan Cerit (2012) juga menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan kompetensi interkultural dapat mengembangkan kompetensi relasional dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, berhasil menyelesaikan konflik yang rumit dengan memindahkan alternatif-alternatif yang muncul sebagai akibat dari perbedaan budaya, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan bisnis dengan rekan-rekan dari budaya yang berbeda.
Holliday (2011) telah menjelaskan bahwa mayoritas orang menganggap kemampuan bahasa sebagai elemen yang paling penting dalam komunikasi antar budaya, tetapi dalam kenyataannya, bahwa unsur saja tidak cukup, karena mereka juga harus memahami ‘silent language’, seperti jarak , persepsi, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lain-lain.
Di sinilah ICC berperan penting karena kompetensi komunikasi antarbudaya saat ini tidak hanya membahas kemampuan berbahasa asing tetapi juga kemampuan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pihak lain untuk menciptakan komunikasi yang efektif.
Chen dan Starosta (1996) mengatakan bahwa warga abad kedua puluh satu harus belajar melihat melalui mata, hati, dan pikiran orang dari budaya selain budaya mereka sendiri. Oleh karena itu, pengembangan ICC menjadi salah satu perhatian utama dalam semua jenis program dan kegiatan, di berbagai bidang, termasuk kesehatan, bisnis, sosial, serta pendidikan.
Di era globalisasi, pendidikan telah mencapai babak baru dimana proses pertukaran ilmu pengetahuan telah melewati batas-batas negara; Salah satu bukti yang bisa dilihat adalah maraknya program pertukaran pelajar yang dilakukan oleh berbagai negara (Chelliah et al., 2019; Findlay et al., 2011).
Sebagian besar universitas dan entitas sosial telah menerapkan berbagai program internasional, termasuk pertukaran pelajar. Mereka mengirim dan menerima mahasiswa dari berbagai negara untuk menciptakan pengalaman internasional jangka pendek, di mana mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diharapkan dapat membimbing mereka dalam dunia bisnis global saat ini (Penbek, ahin, & Cerit, 2012).
Populasi global siswa yang belajar di negara lain berlipat ganda menjadi 5 juta pada tahun 2014 dari 2,1 juta pada tahun 2000, dengan tingkat pertumbuhan 10 persen (Universitas Oxford dalam Chelliah et al., 2019).
Perguruan tinggi di Indonesia sendiri saat ini juga banyak mendapat perhatian dari mahasiswa internasional. Berdasarkan keterangan Patdono Suwignjo, Direktur Jenderal Kelembagaan, Sains, dan Teknologi (dalam Astuti, 2017), sepanjang tahun 2016 telah diterbitkan 6.967 izin belajar, di mana izin belajar merupakan salah satu syarat utama bagi mahasiswa internasional di Indonesia.
Jumlah permohonan izin belajar bagi mahasiswa internasional di sini mengalami peningkatan, menjadi 150-500 permohonan setiap minggunya. Kementerian Riset dan Teknologi dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dalam Arwana, 2016) menargetkan jumlah mahasiswa internasional di Indonesia mencapai 20.000 pada tahun 2019.
Pemilihan suatu negara oleh banyak mahasiswa internasional memang dapat menjadi salah satu bukti bahwa negara tersebut unggul dalam persaingan internasional. Kehadiran mahasiswa internasional di suatu negara menjadi elemen penting dalam internasionalisasi pendidikan tinggi, yang dapat membantu dalam menciptakan keragaman, memfasilitasi pemahaman lintas budaya, menciptakan toleransi, meningkatkan kapasitas penelitian, dan membantu pengembangan lebih lanjut (Guo & Chase, 2011; Maringe & Fosket, 2012).
Karena itu, berbagai negara berlomba-lomba mendatangkan mahasiswa asing untuk belajar di negaranya. Peluang Indonesia untuk mendatangkan mahasiswa asing juga tidak kalah besar dari negara lain (Abidin, 2017).
Namun, jika tidak ada yang dirancang secara khusus, akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan, salah satu faktor kritis yang sering diabaikan, termasuk di Indonesia sebagai negara maju dalam menghadapi mahasiswa asing, adalah kompetensi komunikasi antarbudaya.
Alasan ICC berperan penting dalam bidang pendidikan, khususnya dalam program pertukaran pelajar, adalah karena mahasiswa asing perlu beradaptasi dengan sistem sosial budaya baru yang tentunya berbeda dengan negara asalnya (Yu & Wright, 2016; Wright & Schartner, 2013). ; Gu, Schweisfurth, & Day, 2010). Seperti yang diungkapkan oleh Kim dalam Cai dan Teng (2014), komunikasi memegang peranan penting dalam proses adaptasi ini.
Adaptasi terjadi melalui antarmuka komunikasi antara orang asing dan lingkungan tuan rumah, seperti halnya penduduk asli memperoleh kapasitas mereka untuk berfungsi dalam masyarakat melalui interaksi komunikatif sepanjang hidup mereka. Namun, alih-alih itu, lembaga pendidikan belum sepenuhnya siap mengakomodasi kebutuhan modern tersebut.
Meskipun kajian komunikasi antarbudaya bukanlah hal baru, kepedulian terhadap keragaman budaya baru mendapat perhatian yang signifikan belakangan ini, dimana akhir dari ICC di bidang pendidikan masih sangat rendah dan harus terus digali dan digalakkan (Smakova & Paulsrud, 2020; Fitriyah , Munir, & Retnaningdyah, 2019; Irwandi, 2017).
Topik ini menjadi semakin penting karena program pertukaran pelajar seharusnya memberikan kontribusi lebih dari sekedar manfaat ekonomi (Gareis, 2012). Sebagai negara tuan rumah, Indonesia harus mampu memberikan berbagai pengalaman dan nilai kepada mahasiswa asing. Dengan pengalaman globalnya sendiri, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari citra dan tanggapan positif yang diciptakan berdasarkan pengalaman mahasiswa asing.
Pada akhirnya, mereka dapat memainkan peran penting dalam membina hubungan yang produktif dengan negara tuan rumah, memberikan rekomendasi kepada mitra mereka, dan bahkan berpotensi menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan negara asalnya di masa depan. ICC dapat menjadi keunggulan dalam menyelenggarakan program pertukaran pelajar; sementara itu, faktor-faktor ini sering diabaikan.
Pentingnya peran komunikasi dan interaksi dalam dunia pendidikan, terutama dalam menciptakan pengalaman yang baik bagi mahasiswa asing, telah dibahas oleh berbagai penelitian, yang berdasarkan penelitian sebelumnya, state of the art, Rohrlich dan Martin pada tahun 1991; Searle dan Ward pada tahun 1990 (dalam Gareis, 2012).
Ditemukan bahwa faktor kepuasan utama pertukaran pelajar yang tinggal di suatu negara adalah kontak dan hubungan dengan warga negara tuan rumah. Pelajar asing mengharapkan interaksi ini memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik, peningkatan kinerja akademik, tingkat stres yang lebih rendah, dan kepuasan hidup yang lebih besar.
Dziegielewska pada tahun 1988; Furnham dan Alibhai pada tahun 1985 (dalam Jon, 2013) juga mengatakan bahwa hubungan yang bermakna dengan warga negara tuan rumah membantu proses adaptasi dan memainkan peran penting dalam meningkatkan citra internasional.
Selain itu, Barger pada tahun 2004; Geelhoed, Abe, dan Talbot pada tahun 2003; Nesdale dan Todd pada tahun 2000; Parsons pada tahun 2010; Williams dan Johnson pada tahun 2011 (dalam Jon, 2013) telah menjelaskan dalam penelitian mereka melibatkan siswa internasional dan domestik di AS dan pendidikan tinggi Australia bahwa efek positif dari interaksi mereka pada siswa domestik memiliki efek positif pada pengalaman pendidikan, sosial, dan budaya.
Sayangnya, potensi ini sering tidak disadari, dan salah satu keluhan yang paling menonjol dari mahasiswa yang belajar di luar negeri adalah kurangnya kontak dengan warga negara tuan rumah. Tidak jarang sepertiga atau lebih siswa internasional melaporkan tidak memiliki teman tuan rumah sama sekali (Gareis, 2012).
Berbagai penelitian juga menemukan bahwa mahasiswa domestik dapat merasa tertantang dan enggan berinteraksi dengan mahasiswa internasional karena perbedaan budaya, hambatan bahasa, bias, dan tekanan untuk prestasi akademik (Jon, 2013). Dari sini terlihat bahwa kurangnya kompetensi komunikasi antarbudaya menjadi penyebab utama.
Untuk menciptakan hubungan baik dan mengembangkan ICC, para peneliti menemukan bahwa keterlibatan universitas sangat penting. Perguruan tinggi perlu memahami bagaimana membangun ICC dan menciptakan kenyamanan bagi mahasiswa asing.
Mereka perlu memberikan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pengalaman pribadi dan keterampilan komunikasi yang menyenangkan dan produktif bagi pesertanya. Menjadikan program pertukaran pelajar sebagai kegiatan yang meskipun singkat, menjadi sarana untuk menciptakan perubahan positif yang dapat dikenang seumur hidup.
Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan negara sebagai tujuan pendidikan. Namun, penelitian terkait kesadaran ICC dan implementasinya masih sangat minim, terutama di negara maju.
Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh tentang Kompetensi Komunikasi Antarbudaya berdasarkan pengalaman mahasiswa asing di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait ICC berdasarkan pengalaman mahasiswa asing, tantangan yang dihadapi, dan cara mengatasinya.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk lebih mengevaluasi ICC dalam konteks pendidikan yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kompetensi di kalangan siswa dengan melihat urgensi dan pentingnya peran ICC di berbagai sektor.
Penelitian ini didukung oleh beberapa teori dan konsep. Teori pertama yang digunakan adalah komunikasi antarbudaya. Menurut Neuliep (2018), komunikasi antar budaya terjadi di mana minimal dua orang dari budaya atau mikrokultur yang berbeda berkumpul dan bertukar simbol verbal dan nonverbal. Itu terjadi di dalam dan di antara berbagai konteks yang saling terkait, termasuk konteks budaya, mikrokultur, lingkungan, persepsi, dan sosiorelasional (Neuliep, 2018).
Hal ini merupakan aktivitas komunikasi antara orang-orang dengan keyakinan, nilai, dan norma yang berbeda, di mana semua pesan berasal dari konteks budaya yang unik atau spesifik (Devito dalam Nurhadi, Hendrawan, & Ayutria, 2019). Menurut Effendy (2017), komunikasi antarbudaya terjadi dalam dua bentuk, yaitu komunikasi pribadi (komunikasi yang terjadi antara dua orang) atau komunikasi kelompok komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan sekelompok atau sekelompok orang).
Tuleja (2016) juga menambahkan dengan mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai pertukaran komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Ini meneliti bagaimana perbedaan budaya tertentu mempengaruhi interaksi orang-orang yang terlibat.
Sedangkan terkait dengan fungsi komunikasi antarbudaya, Liliweri (2014) telah menjelaskan beberapa fungsi, antara lain fungsi personal (menyatakan identitas sosial, mengungkapkan integrasi sosial, menambah pengetahuan) dan fungsi sosial (pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, menghibur).
Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi komunikasi antarbudaya. Kajian tentang ICC atau komunikasi antarbudaya bermula dari karya ilmuwan politik dan antropolog pada tahun 1940-1950-an (Chen & Starosta, 1996). Dinyatakan bahwa hanya melalui komunikasi antar budaya yang kompeten, orang-orang dari budaya yang berbeda dapat berkomunikasi secara efektif dan tepat dalam masyarakat global yang akan datang.
Liu, Volcic, dan Gallois (2014) menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya terjadi untuk setiap pesan yang dihasilkan oleh anggota suatu budaya untuk dikonsumsi oleh anggota budaya lain. Komunikasi antarbudaya menghadapi berbagai masalah dan tantangan karena setiap anggota budaya tentunya memiliki cara berkomunikasi dan berpikir yang berbeda. Dengan demikian, ICC menjadi arah untuk menganalisis interpretasi, motivasi, dan keterampilan komunikator dalam komunikasi antarbudaya.
Setelah mengkaji berbagai pendekatan mengenai ICC, ditemukan model bangunan interaktif-multikultural (Chen & Starosta, 1996). Model ini digunakan untuk menjelaskan proses-proses yang ada dari tiga perspektif berbeda yang sama-sama penting, tidak terpisahkan, dan membentuk gambaran kompetensi komunikasi antarbudaya.
Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami, menghargai, menoleransi, dan mengintegrasikan perbedaan budaya sehingga siap menjadi anggota masyarakat dunia (Chen & Starosta, 1996). Menyajikan proses transformasi saling ketergantungan simetris, yang dijelaskan melalui tiga perspektif (Chen & Starosta, 1996; Chen & Starosta, 2000; Chen, 2010).
Perspektif pertama adalah proses afektif (kepekaan antarbudaya). Perspektif ini berfokus pada emosi pribadi atau perubahan perasaan yang disebabkan oleh situasi, orang, dan lingkungan tertentu. Empat atribut dasar yang membangun perspektif ini adalah konsep diri (cara seseorang melihat dirinya sendiri), open mindedness (keinginan individu untuk mengekspresikan diri secara terbuka dan menerima penjelasan orang lain), sikap tidak menghakimi (tidak memiliki prasangka yang dapat merugikan).
Mencegah seseorang dari mendengar orang lain selama komunikasi antar budaya), dan relaksasi sosial (kemampuan untuk mengekspresikan kecemasan atau ketakutan dalam komunikasi antar budaya). Perspektif kedua adalah proses kognitif (kesadaran antarbudaya). Perspektif ini menekankan bagaimana cara berpikir orang tentang lingkungan proses ini, individu dituntut memiliki self awareness (kemampuan individu untuk memonitor dan membuat dirinya sadar) dan cultural awareness (pemahaman terhadap budaya sendiri dan orang lain yang mempengaruhi cara orang berpikir dan berperilaku).
Perspektif terakhir adalah proses perilaku (intercultural adroitness). Perspektif ini menekankan bagaimana individu bertindak secara efektif dalam interaksi antar budaya. Perspektif ini erat kaitannya dengan keterampilan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk memberikan interaksi yang efektif.
Atribut yang membangun perspektif ini adalah keterampilan pesan (kemampuan untuk menggunakan bahasa suatu budaya di luar budayanya sendiri), pengungkapan diri yang tepat (kemauan untuk mengungkapkan informasi secara terbuka dan tepat selama interaksi antarbudaya), fleksibilitas perilaku (kemampuan untuk memilih yang sesuai).
Perilaku dalam konteks dan situasi yang berbeda, manajemen interaksi (kemampuan untuk berbicara bergantian dalam percakapan, memulai, dan mengakhiri percakapan dengan benar), dan keterampilan sosial (empati, kemampuan untuk merasakan emosi yang sama dengan orang lain dan pemeliharaan identitas, menjaga identitas orang lain dalam interaksi).
Konsep terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah internasionalisasi pendidikan tinggi. Internasionalisasi pendidikan tinggi mencakup berbagai strategi atau kegiatan yang dirancang untuk memasukkan pendidikan internasional ke dalam kurikulum yang ada (Maringe & Foskett, 2012) dengan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, perekrutan mahasiswa internasional, dan pengembangan kemitraan.
Internasionalisasi pendidikan tinggi itu sendiri didefinisikan oleh Ellingboe (sebagaimana dikutip oleh Gopal, 2011) sebagai proses kompleks yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif internasional ke dalam institusi pendidikan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai respon dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang semakin beragam, global, dan berubah. Zolfaghari dan Sabran dalam Gopal
(2011) juga menggambarkan internasionalisasi pendidikan tinggi sebagai integrasi dan infus dimensi internasional sebagai bagian sentral dari program universitas. Senada dengan itu, Knight dalam Bedenlier dan Zawacki-Richter (2015) menggambarkannya sebagai proses mengintegrasikan dimensi internasional ke dalam fungsi pengajaran/pembelajaran, penelitian, dan layanan universitas atau perguruan tinggi.
Pembahasan
Ketika manusia menghadapi keragaman budaya yang lebih besar, kompetensi komunikasi antar budaya menjadi semakin penting. Hanya dengan kompetensi ini, orang-orang dari budaya yang beragam mampu memahami satu sama lain sepenuhnya.
Sebagai upaya untuk mengetahui kompetensi tersebut, dilakukan penelitian untuk melihat lebih jauh Intercultural Communication Competence (ICC) berdasarkan pengalaman mahasiswa asing di Indonesia, tantangan yang dihadapi, dan cara mengatasinya. Pendekatan kajian kompetensi komunikasi antarbudaya yang dibahas kemudian mengarah pada model tiga perspektif yang dijadikan fokus penelitian.
Perspektif pertama adalah proses afektif (kepekaan antarbudaya). Perspektif ini berfokus pada emosi pribadi atau perubahan perasaan yang disebabkan oleh situasi, orang, dan lingkungan tertentu (Chen & Starosta, 1996; Chen & Starosta, 2000; Chen, 2010).
Terkait dengan hal tersebut, mahasiswa internasional di Indonesia menggambarkan kemampuannya dalam mengendalikan emosi dan perasaannya yang disebabkan oleh situasi, orang tertentu, dan lingkungan berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan program pertukaran pelajar di Indonesia.
Delapan dari sepuluh siswa yang diwawancarai mengaku memiliki kemampuan ini, di mana mereka menjelaskan bahwa emosi pribadi atau perubahan perasaan pasti terjadi setiap saat. Namun, ketika mereka menghadapi berbagai perbedaan budaya ketika tinggal di negara lain, perasaan ini lebih sering muncul karena beberapa hal yang cukup mengganggu atau berbeda dari budaya asli mereka.
Salah satu mahasiswa asal Jerman dari Universitas Rhine Waal membahas bagaimana dia merasa tidak nyaman ketika orang-orang di Jakarta sering memfilmkannya tanpa izin. Hal serupa juga dialami mahasiswa Lithuania dari Hanze University of Applied Sciences, Groningen, The Netherland.
Ia menyatakan bahwa banyak orang Indonesia yang tidak menghargai ruang privat dan bahkan tidak mengerti apa itu ruang privat; Orang-orang selalu meminta/berteriak untuk berfoto di setiap sudut Jakarta (komunikasi pribadi, 22 Januari 2020).
Sedangkan dalam konteks akademik, mahasiswa dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universitas Hanze menjelaskan bahwa emosi dan perasaan mereka sering berubah karena harus menghadapi tantangan baru, orang, lingkungan, dan suasana di kelas. Mereka berpikir bahwa kelas di Indonesia sangat bising, di mana orang-orang berteriak atau bernyanyi selama kelas, dan itu sangat normal bagi siswa lokal. Oleh karena itu, mereka merasa tidak profesional dan tidak menghormati dosen dan mahasiswa lainnya.
Namun, terlepas dari semua perubahan dan ketidaknyamanan yang mereka hadapi, sebagian besar peserta pertukaran pelajar yang diwawancarai mengakui bahwa mereka masih dapat mengelola dan menangani perubahan secara profesional. Mereka menunjukkan hal ini dengan tidak marah atau frustrasi, melainkan dengan ramah meminta orang Indonesia untuk berhenti atau menjelaskan bahwa budaya mereka berbeda.
Kemampuan tersebut juga mereka buktikan dengan menggambarkan bagaimana mereka mampu mempertahankan ekspresi wajah mereka dengan tidak menunjukkan ketidaksukaan saat menghadapi perbedaan dan kesulitan.
Selain itu, dua siswa lainnya menjelaskan bahwa mereka pikir mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki banyak kesempatan yang membuktikan bahwa mereka tidak dapat melakukannya.
Mereka menyadari fakta bahwa memahami suatu budaya memang membutuhkan banyak kesabaran, dan berasal dari negara dengan budaya yang berbeda membuat sulit untuk menghindari pertimbangan emosi dalam kehidupan sehari-hari.
Mahasiswa Jerman dari The Hague University ini juga menambahkan bahwa butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa orang Indonesia sangat sensitif dan perasaan harus dihindarkan, yang sedikit membuat frustrasi di awal perjalanan studinya.
Perspektif selanjutnya adalah proses kognitif (kesadaran antarbudaya). Perspektif ini menekankan pada perubahan pemikiran seseorang tentang suatu lingkungan dengan memahami perbedaan karakteristik budaya masyarakat (Chen dan Starosta, 1996).
Terkait dengan perspektif ini, semua mahasiswa asing yang diwawancarai mengklaim bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengubah cara berpikir mereka dengan memahami keragaman dan budaya orang lain. Bahkan mereka menganggap bahwa ini sudah menjadi kebutuhan ketika mereka belajar di negara lain.
Hal ini umumnya terjadi karena mereka telah memiliki pengalaman sebelumnya, baik karena terbiasa hidup dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan yang berasal dari berbagai bangsa dan pengalaman tinggal di luar negeri. Contohnya adalah pernyataan dari mahasiswa Jerman dari Universitas Rhine Waal.
“Untuk berkomunikasi dengan budaya lain, Anda harus memahaminya. Berasal dari negara di mana keragaman begitu luas, sudah menjadi sifat saya untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Keluarga saya sendiri adalah campuran”
Seorang mahasiswa Lithuania dari Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Belanda juga menambahkan bahwa untuk memiliki kemampuan ini.
“Sering kali saya mencoba membaca pikiran dari apa yang dikatakan orang, mencoba membayangkan diri saya di posisi mereka jika saya ingin memahami budaya dan tradisi orang lain.nonverbal Komunikasi adalah aspek budaya dan sulit untuk kehilangan itu, jadi saya tidak keberatan bahwa orang yang menggunakan satu atau isyarat lain menuju sendiri, hanya karena aku tahu seseorang yang dapat tersinggung dengan komunikasi non-verbal budaya saya sendiri.” (Pinariya & Sutjipto, 2021)
Perspektif terakhir adalah proses perilaku (intercultural adroitness). Perspektif ini menekankan bagaimana individu bertindak secara efektif dalam interaksi antar budaya. Perspektif ini erat kaitannya dengan keterampilan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk memberikan interaksi yang efektif (Chen dan Starosta, 1996).
Serupa dengan persepsi sebelumnya, semua mahasiswa asing yang diwawancarai mengakui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya lain, baik secara verbal maupun non-verbal.
Hal ini umumnya terjadi karena meskipun ada banyak situasi di Indonesia ketika orang tidak dapat memahaminya atau sebaliknya, mereka masih dapat secara konsisten memenuhi kebutuhannya. Mahasiswa Jerman dari The Hague University menjelaskan bahwa ketika bahasa Inggris tidak berfungsi, mereka menggunakan komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan atau ekspresi wajah untuk menjelaskan dan berkomunikasi.
“Berasal dari keluarga dan negara yang beragam, saya berbicara dalam tujuh bahasa. Selama mempelajari banyak bahasa itu, saya juga belajar bahwa tidak cukup hanya mempelajari kata-kata tetapi juga mempelajari rangkaian pemikiran, tindakan, dan gerak tubuh. Oleh karena itu, saya merasa cukup nyaman untuk jatuh ke dalam budaya orang lain selama saya memahaminya; namun, berusaha untuk tidak membuat stereotip.” (Pinariya & Sutjipto, 2021)
Secara umum, semua mahasiswa asing yang diwawancarai mengaku sudah memiliki kompetensi untuk melakukan komunikasi antarbudaya berdasarkan ketiga perspektif tersebut. Namun, pernyataan sebaliknya datang dari empat teman sekelas Indonesia Mereka menjelaskan bagaimana berdasarkan pengalaman mereka, mereka dapat melihat bagaimana peserta pertukaran pelajar sering terlihat kesal dan memberikan sikap terhadap orang yang dekat dengan mereka.
Teman-teman Indonesia juga menambahkan bahwa beberapa mahasiswa asing terlihat marah karena bahasa Indonesia tidak to the point dan tidak tepat waktu. Selain ketiga perspektif tersebut, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya dalam menerapkan kompetensi komunikasi antarbudaya berdasarkan pengalaman mahasiswa internasional di Indonesia.
Berdasarkan pernyataan tersebut, masih terdapat ketidaksetaraan dan perbedaan pendapat serta penilaian kompetensi komunikasi antarbudaya, dimana mahasiswa asing merasa sudah memiliki kemampuan komunikasi antarbudaya yang baik, namun di sisi lain mahasiswa tuan rumah memiliki pendapat yang berbeda.
Perbedaan penilaian dan standar tersebut kemudian menunjukkan bahwa pelatihan, informasi, dan program khusus diperlukan untuk menciptakan persepsi yang sama tentang ICC, serta mempersiapkan siswa yang akan melakukan program pertukaran, baik di negara asal maupun di negara tujuan.
Tim universitas juga menjelaskan bahwa beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar secara umum adalah mengenai bahasa yang digunakan oleh para pengajar sebagai kendala faktor akademik.
Sedangkan hambatan dalam faktor sosial sering terjadi karena perbedaan budaya yang seringkali memicu kesalahpahaman. Tim juga mengakui bahwa sebagian besar peserta pertukaran pelajar di Indonesia tidak memiliki teman dekat.
Sedangkan terkait kelemahan dan kelebihan yang dimiliki peserta pertukaran pelajar, tim dari berbagai negara menjelaskan bahwa mahasiswa asing dari negara Asia lainnya tidak memiliki masalah atau kelemahan karena budaya mereka pada umumnya mirip dengan budaya Indonesia.
Sedangkan bagi mahasiswa dari negara lain di luar Asia, kesadaran budaya menjadi kelemahan utama mereka. Banyak mahasiswa yang masih belum mengetahui banyak tentang budaya Indonesia dan memiliki beberapa bias.
Sedangkan terkait program yang dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada, student exchange yang diwawancarai menjelaskan bahwa tidak ada program khusus yang ditujukan untuk mempersiapkan mereka. Hal ini kemudian ditegaskan oleh perguruan tinggi, baik dari Indonesia maupun perguruan tinggi mitra asing.
Namun, beberapa kegiatan atau upaya umum dilakukan, yang terbagi menjadi online dan konvensional. Sedangkan untuk kegiatan online, universitas memanfaatkan penggunaan berbagai media sosial untuk memberikan informasi mengenai program pertukaran, antara lain Instagram, postingan Facebook, email, dan website.
Sedangkan untuk kegiatan offline, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah briefing (pra pemberangkatan & selama), program orientasi sehari yang membahas tentang negara, kota, bahasa, budaya, tradisi, akademik (info tentang kegiatan akademik sesi online), poster kampus, rekomendasi dari penasihat mereka, kunjungan kelas, tur kota, dan badan mahasiswa.
Diakui pula oleh mahasiswa, baik Indonesia maupun asing, bahwa peran dan keterlibatan pemerintah Indonesia terkait pengembangan kompetensi komunikasi antarbudaya masih dianggap pasif. Pemerintah Indonesia hanya berpartisipasi dan mengarahkan siswa untuk mengetahui pengetahuan dasar tanpa disertai dengan pelatihan keterampilan komunikasi khusus.
Dengan bantuan atau peran serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama, perguruan tinggi seharusnya dituntut atau diarahkan untuk membentuk program khusus terkait ICC, baik yang ditujukan kepada masyarakat asing maupun Indonesia sebagai target audience-nya.
Ini bisa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membantu Indonesia menjadi tujuan pendidikan yang siap dan diinginkan. Dari sini, sekali lagi terbukti bahwa ICC belum menjadi prioritas dan mendapat perhatian yang cukup dari berbagai pihak, seperti mahasiswa, universitas, dan pemerintah.
Karena upaya mempersiapkan mahasiswa asing sudah menjadi kebutuhan, maka peneliti merekomendasikan agar ada program seperti sosialisasi bagi mahasiswa intensional, terutama untuk memahami budaya dan menguasai kompetensi komunikasi antarbudaya setidaknya di negara tujuan.
Untuk memaksimalkan strategi yang digunakan untuk mengembangkan ICC, diperlukan bantuan atau dukungan dari berbagai pihak, di antaranya universitas sebagai institusi utama yang memberikan layanan, mahasiswa asing sebagai aktor utama yang terlibat dalam kegiatan komunikasi antarbudaya, teman sebagai asisten dan narasumber, dan pemerintah sebagai fasilitator yang dapat memainkan peran vital dalam menentukan regulasi yang dalam berbagai hal dapat mempengaruhi perkembangan ICC.
Secara keseluruhan, selain semua permasalahan yang dihadapi, mahasiswa asing merasa cukup puas memilih Indonesia sebagai tujuan studi dan merekomendasikan Indonesia kepada mahasiswa lain yang akan melakukan program pertukaran pelajar di masa mendatang.
Namun, mereka menjelaskan bahwa rekomendasi ini hanya berlaku jika mahasiswa tidak ingin memperluas pengetahuan universitas mereka tetapi pengalaman petualangan, komunikasi, sosial, dan keterampilan pribadi dalam hidup mereka.
Mereka merekomendasikan Indonesia jika prioritasnya adalah bepergian daripada mendapatkan pendidikan kelas atas. Sementara itu, mitra universitas asing menjelaskan bahwa alasan mereka memilih Indonesia karena beberapa alasan, antara lain keragaman budaya, potensi untuk menjadi negara terkemuka di kawasan atau global, menawarkan lebih banyak pilihan kepada mahasiswanya, untuk memperkuat koneksi dengan mitra ASEAN, keamanan, bahasa, dan mata uang.
Kesimpulan
Dengan perubahan yang ada, manusia dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang semakin kompleks dalam menciptakan interaksi yang tepat dan efektif dalam keragaman. Salah satu keterampilan khusus dan esensial yang dibutuhkan dalam menghadapi perbedaan budaya, yaitu Intercultural Communication Competence (ICC).
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh ICC berdasarkan pengalaman mahasiswa asing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait ICC berdasarkan pengalaman mahasiswa asing, tantangan yang dihadapi, dan cara mengatasinya.
Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar siswa beranggapan bahwa mereka memiliki ICC baik terkait dengan unsur-unsur dalam proses afektif, kognitif, dan perilaku. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mereka berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka temui selama tinggal di Indonesia.
Namun masih terdapat ketidaksetaraan dan perbedaan pendapat serta penilaian kompetensi komunikasi antarbudaya, dimana pernyataan bertolak belakang berasal Indonesia yang merupakan teman sekelas.
Mereka menjelaskan bagaimana berdasarkan pengalaman mereka, mereka bisa melihat bagaimana peserta pertukaran pelajar sering terlihat kesal dan memberikan sikap terhadap orang yang dekat dengan mereka.
Teman-teman Indonesia juga menambahkan bahwa beberapa mahasiswa internasional terlihat marah karena bahasa Indonesia tidak to the point dan tidak tepat waktu. Tim universitas juga menjelaskan bahwa beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar secara umum adalah mengenai bahasa yang digunakan oleh para pengajar sebagai kendala faktor akademik.
Sedangkan hambatan dalam faktor sosial sering terjadi karena perbedaan budaya yang seringkali memicu kesalahpahaman. Tim juga mengakui bahwa sebagian besar peserta pertukaran pelajar di Indonesia tidak memiliki teman dekat.
Menanggapi permasalahan yang ada, tidak ada program khusus yang ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa (baik Indonesia maupun asing) mapun oleh asalnya universitas, ataupun pemerintah.
Terbukti ICC belum menjadi prioritas dan belum mendapat perhatian yang cukup dari berbagai pihak. Karena upaya mempersiapkan mahasiswa asing sudah menjadi kebutuhan, maka perlu adanya program seperti sosialisasi bagi mahasiswa yang intensional, terutama untuk memahami budaya dan menguasai kompetensi komunikasi antarbudaya, setidaknya di negara tujuan.
Untuk memaksimalkan strategi yang digunakan untuk mengembangkan ICC, diperlukan bantuan atau dukungan dari berbagai pihak, di antaranya universitas sebagai institusi utama yang memberikan layanan, mahasiswa asing sebagai aktor utama yang terlibat dalam kegiatan komunikasi antarbudaya, teman sebagai asisten dan narasumber, dan pemerintah sebagai fasilitator yang dapat memainkan peran vital dalam menentukan regulasi yang dalam berbagai hal dapat mempengaruhi perkembangan ICC.
Indonesia belum menjadi prioritas dan mendapat perhatian yang cukup dari berbagai pihak, baik mahasiswa, universitas, maupun pemerintah. Dimana pertimbangan dan tantangan terhadap kompetensi ini masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mencapai hasil yang maksimal dalam konteks komunikasi antarbudaya. (**)